Menelisik Kekeluargaan di Jalan Bandungan
Setiap
orang memiliki harapan yang besar dalam kehidupan rumah tangganya. Namun,
kehidupan rumah tangga yang dijalani Muryati dan Widodo tidak seperti apa yang
dibayangkan orang-orang di sekitarnya, juga tidak seperti kehidupan kedua orang
tuanya. Muryati dibesarkan oleh orang tua yang begitu mengedepankan kebahagiaan
anggota keluarganya dengan melakukan berbagai hal, seperti menonton film
bersama hingga mengunjungi tempat liburan setiap akhir pekan. Setelah menikah
dengan Widodo—anak buah ayahnya pada masa revolusi—Muryati merasakan banyak hal
yang salah pada kehidupan rumah tangganya.
Kisah
ini dimulai dengan penggambaran kondisi di akhir novel—masa ketika Muryati
sudah menikah dengan adik Widodo, Handoko—sebelum melakukan kilas balik yang
menceritakan kronologi mulai dari masa kecil Muryati hingga kompleksnya
kehidupannya ketika dewasa dan berumah tangga. Seluruh cerita dalam novel ini
berdasarkan sudut pandang Muryati. Akan berbeda atmosfer sudut pandang Muryati
ketika masih duduk di bangku Sekolah Rakyat dan ketika ia telah berumah tangga.
Tentang kehidupan masa revolusi, pergaulan dan persahabatan di sekolah, hingga
rasa penasaran para remaja mengenai pergaulan lawan jenis diungkapkan di
masa-masa muda Muryati. Hal kompleks mulai muncul ketika ia dekat dengan Widodo
yang cukup dingin untuk dirinya yang terbiasa hidup dalam keluarga yang bahagia
hingga Muryati menjadi seorang yang begitu pasif setelah menikah dengan Widodo.
Sukar
bagi Muryati untuk keluar dari kungkungan status istri yang hanya diberi jatah
untuk melakukan pekerjaan di kasur, sumur, dan dapur dengan jatah nafkah yang
kecil pula. Tiada kebahagiaan yang ia dapatkan dari Widodo selain rasa sakit
karena percintaan mereka hanya untuk kepuasan batin Widodo saja. Sempat Muryati
berpikir untuk kembali mengajar seperti ketika ia belum menikah untuk menambah
uang saku dalam keluarganya, namun dilarang sang suami. Untuk berbicara pun,
Muryati selalu diabaikan. Hingga pada suatu hari, sang suami hilang dan
ditemukan telah dipenjara dikarenakan menjadi anggota Partai Komunis.
Sesekali
saya sempat berpikir bahwa terlalu dini untuk saya memahami pengalaman berumah
tangga lewat “Jalan Bandungan”. Novel ini cukup lama saya baca karena sering
mengulur waktu, dari akhir Agustus hingga akhir Oktober, nyaris dua bulan.
Dalam waktu yang panjang tersebut, saya justru menemukan berbagai relasi antara
kisah di novel ini dengan apa yang saya temukan di dunia nyata. Bahwa hubungan
percintaan antar laki-laki dan perempuan begitu kompleks dan betapa patriarki
yang sudah tertanam di dalam masyarakat tak jarang merugikan perempuan, seperti
pada kasus pasca Widodo ditahan. Betapa Muryati begitu sukar mendaftarkan diri
sebagai pengajar dan berjuang membesarkan anak di bawah stigma “istri seorang
komunis”. Betapa status “istri seorang komunis” dan dituduh “gerwani” juga
sempat mempersulit jalannya untuk melanjutkan pendidikan di negeri seberang.
Padahal, sekali pun ia tak pernah terlibat alih-alih berkesempatan mendengar
cerita dari sang suami yang tertutup dan sering abai terhadapnya, terutama
mengenai cuti dari kantor hingga menjadi anggota partai terlarang pada masa
itu.
Kisah
ini juga menggambarkan kesetiaan lima sekawan—Muryati, Murniyah, Ganik, Sri,
dan Siswi—dari masa sekolah hingga dewasa dan berumah tangga. Kehidupan Muryati
pasca menjadi istri seorang tahanan politik membuatnya kembali dekat dengan
keluarganya dan para sahabatnya. Bahkan ia juga sowan ke rumah mertuanya yang tak pernah ia temui selama menikah
dengan Widodo. Dalam perjalanan hidup Muryati di novel ini, hubungannya dengan para sahabatnya begitu dekat seperti keluarga sendiri. Ketika Muryati menghadapi persoalan serius dalam hidupnya, para sahabat dan orang tua sahabatnya bahu membahu membantunya dalam menyelesaikan masalah.
Satu diantara alasan mengapa judul novel ini adalah "Jalan Bandungan" karena permasalahan terbesar dalam novel ini terjadi ketika Muryati telah tinggal di Jalan Bandungan, tepatnya di rumah yang menjadi peninggalan Ganik dan orang tuanya, Dokter Liantoro dan istri. Permasalahan yang cukup krusial itu disebabkan oleh mantan suami Muryati, Widodo.
Mulanya
sebelum membaca “Jalan Bandungan” dan karya Nh. Dini lainnya yang bertajuk “Keberangkatan”,
saya tidak memiliki gambaran mengenai kehidupan generasi masa 20 hingga 30
tahun pasca kemerdekaan. Meski akhirnya saya mengetahui betapa majunya pikiran
orang-orang yang menjadi tokoh di novel-novelnya, saya juga menyadari bahwa
yang tengah diceritakan adalah orang-orang urban di Jawa pada masa tersebut. Sedikit
banyak saya mempelajari bahwa perempuan pada masa itu semakin progresif
pikirannya mengenai hak-hak perempuan—bahwa perempuan tidak hanya sekadar bekerja
di sumur, dapur, dan kasur. Sesekali Muryati juga mengeluhkan betapa tidak
berdayanya perempuan dalam memberikan keputusan.
Kisah
Muryati ini dekat sekali dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Saya sendiri
paham betul dalam dua bulan belakangan ini ketika terlibat langsung dalam
permasalahan yang sama kompleksnya dengan apa yang Muryati alami. Ketika di
novel sebelumnya saya menemukan perasaan emosional seorang perempuan yang
ditinggal menikah oleh kekasihnya, novel “Jalan Bandungan” ini lebih
menunjukkan perjuangan lahir dan batin seorang perempuan membesarkan anaknya
seorang diri, bersama dukungan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang sudah
seperti keluarga sendiri. Pada kisah ini juga terdapat hubungan rumit
percintaan orang dewasa yang mau tidak mau terlibat ketika ada permasalahan
dalam keluarga.
Pernah
saya tertarik pada sebuah pesan dari dosen saya, bahwa membaca sastra
menciptakan empati pada pembacanya. Selain merasakan apa yang dirasakan Muryati
pada novel ini, sedikit banyak saya juga belajar dari pemikiran kritis seorang
Muryati dalam menghadapi permasalahan yang menimpanya.[]
Resensi Jalan Bandungan NH Dini, Review Jalan Bandungan
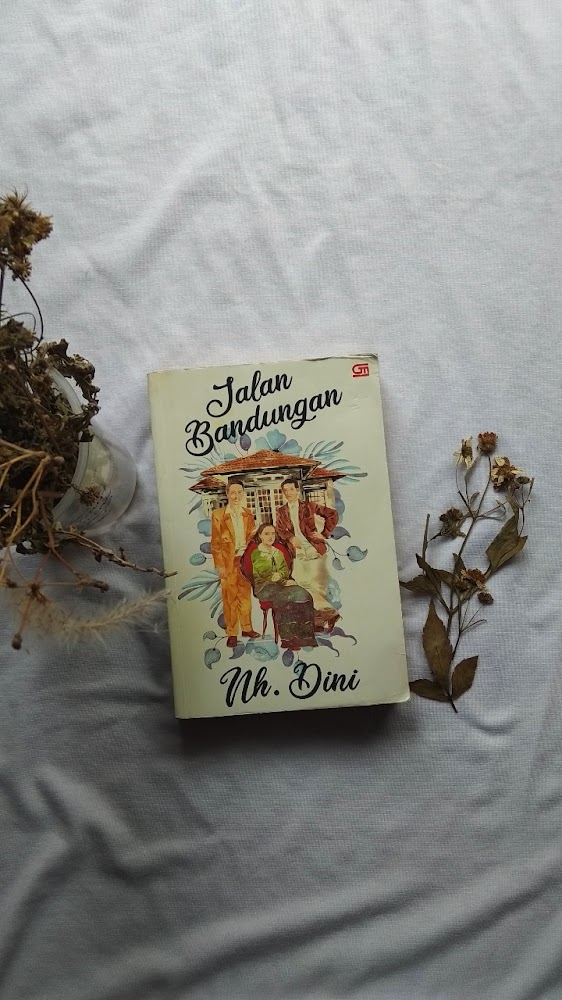



Comments
Post a Comment